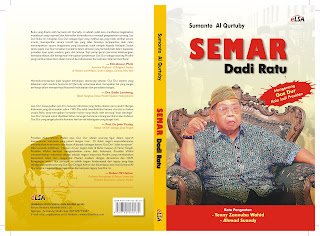Ada
sebuah riwayat dari Ibnu Abbas tentang pengusiran terhadap Bani Nadlir dari
Madinah atas tuduhan penghianatan yang dilakukan. Di antara mereka, ternyata ada
anak-anak muda dari kaum Anshar yang berada dalam kelompok bersama orang-orang
Yahudi. Melihat kejadian ini, sebagian kaum Anshar kemudian berkata, “Jangan kita
biarkan anak-anak kita bersama mereka.” Cerita ini termasuk satu dari sekian riwayat
yang menjadi sebab turunnya QS al-Baqarah: 256. Ayat ini pun lantas dijadikan pondasi
tekstual mengenai kebebasan beragama, (M. Najibur Rohman, 2010).
Bahkan dalam suatu waktu, Nabi Muhammad dikejutkan dengan berita yang
memuat seorang non-Muslim dibunuh oleh seorang Muslim. Mendengar ini, Nabi
sangat marah. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang menyakiti non-Muslim yang
berdamai dengan Muslim, maka aku memusuhinya, dan orang yang memusuhinya, maka
di hari kiamat, dia bermusuhan denganku," (HR Ibnu Masud). Dalam
keterangan hadis lain ditegaskan bahwa, “barangsiapa yang membunuh non-Muslim
tanpa alasan yang benar, maka Allah benar-benar melarang baginya masuk surga,”
(HR Ibnu Umar).
Demikianlah
secara tegas ajaran Islam ketika menjaga kebebasan beragama. Ia membentengi
dengan cara-cara kemanusiaan. Akibatnya, umat Islam tidak diperkenankan
memaksakan agama kepada penganut agama lain, kepada orang lain. La ikraaha
fi al-diin, tidak ada paksaan di dalam agama. Prinsip kebebasan inilah yang
kemudian mendasari pemikiran-pemikiran progresif untuk menempatkan agama dalam
ruang yang lebih harmonis.
Di
Indonesia, kebebasan beragama diatur sedemikian rupa dalam konstitusi negara. Undang-Undang
Dasar memberi penjelasan kepada semua orang untuk beribadah sesuai agama dan
kepercayaan masing-masing. Pancasila juga serupa, ia yang terus mengkampanyekan
bahwa “Negara Indonesia berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
Relevansi
dari rumusan dasar itu kemudian dibingkai pemerintah dengan membentuk sebuah
departemen yang khusus menangani masalah Agama dan keyakinan, Kementerian Agama
(dulu Depag). Sayangnya, dalam hal ini pemerintah nampak tidak adil. Ia hanya menghargai
dan mengakui keberadaan agama-agama besar yang mempunyai basis massa dan agama
yang mempunyai legitimasi dalam menentukan arah stabilitas politik.
Pemerintah
agaknya membatasi hak masyarakat sipil dengan membingkai agama-agama besar dalam
naungan yang direstui negara, alias legal, sah. Sedangkan agama-agama lain, semisal
agama lokal, agama bumi, dianggap ilegal. Dari sini, bisa dilihat ketika pemerintah
memberikan pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di kementerian Agama kepada enam
agama besar: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Selain
agama-agama itu, nampak pemerintah memilih bersikap acuh.
Memang
tidak ada data statistik yang bisa diandalkan ketika menelisik wawasan
keberagamaan yang dianut warga. Data dari laporan kebebasan beragama
Internasional yang diterbitkan Biro Demokrasi, Hak-Hak Asasi dan Perburuhan menunjukkan
bahwa 87 persen populasi adalah Muslim; 6 persen Protestan; 3,6 persen Katolik;
1,8 persen Hindu; 1 persen Buddha; dan 0,6 persen memeluk keyakinan ‘lain’,
termasuk di dalamnya kepercayaan tradisional penduduk asli, kelompok Kristen
lain, dan Yahudi. Meski demikian, komposisi pemeluk agama di negara ini lebih
cenderung pada permasalahan politis. Betapa tidak, pemeluk agama Kristen,
Hindu, dan pemeluk keyakinan minoritas lain mempercayai statistik itu mengecilkan
angka yang sesungguhnya dari jumlah warga non-Muslim.
Hal
yang paling nampak ketika Hukum Positif mengharuskan warga negara yang sudah
dewasa untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di dalamnya mewajibkan
untuk dicantumkan agama yang dipeluk seseorang. Pada masa itu, tidak ada
pembicaraan yang kompromistis. Seperti halnya kaum animis ataupun ateis yang
dipaksa harus mengakui salah satu agama tertentu. Kenyataan dari yang ada, banyak
dari mereka yang dicatat sebagai Muslim, karena Islam adalah agama mayoritas.
* * * * * * * * *
Padahal
sebelas tahun lalu, Indonesia telah meratifikasi lahirnya Undang-Undang RI
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang didalamnya memuat hak kebebasan beragama.
Indonesia juga telah meloloskan terbentuknya UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Peradilan Hak Asasi Manusia. Setidaknya lewat dua aturan hukum itu, payung
hukum terkait Hak Asasi Manusia menjadi kian jelas. Namun, ada anggapan bahwa
penyelesaian konflik HAM hanya bersifat semu. Padahal negara, secara resmi,
mengakui HAM yang tertuang dalam salah satu pasal UU HAM. Lebih dari itu, Indonesia pun telah masuk sebagai bagian dari dunia
yang juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, meski ia belum meratifikasi
Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik (the International Covenant
on Civil and Political Rights).
Tak
pelak, aturan yang mengundang ‘diskriminalitas’ itu digugat berbagai kalangan.
Lewat Mahkamah Konstitusi, mereka yang merasa dirugikan menggugat Undang-undang
No. 1/PNPS/1965 yang genesisnya berasal dari Penetapan Presiden No. 1 Tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. PP ini sendiri
ditetapkan oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden RI di Jakarta pada 27 Januari
1965.
Memang
dalam banyak hal, isi dari PNPS 1965 ini sangat dilematis dan rancu. Satu sisi,
ia terdapat upaya melindungi kebebasan beragama. Akan tetapi, di sisi lain, ia
lebih mengarah pada "intimidasi" kepada kelompok minoritas. Pada
penjelasan umum item 2 misalnya, disebutkan, "di antara
ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah
banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan
nasional dan menodai agama, dan telah berkembang ke arah yang sangat
membahayakan agama-agama yang ada.”
Di
sinilah mengapa problem yang bersumber dari PNPS No.1 Tahun 1965 ini muncul dan
selalu bermasalah, bersifat dilematis. Meski pada sidang di MK tahun lalu ,
gugatan mencabut UU itu ditolak secara judisial review. Namun, bagi
mereka yang tetap mempercayai UU ini dihapus, masih ada sosial review yang
justru jauh lebih penting daripada landasan hukum. Maka, di sinilah perlu
pemetaan yang jelas terkait keberpihakan negara terhadap jaminan
kebebasan beragama. Apakah negara serius melakukan demografi kebebasan
beragama? Jika iya, hal ini pada akhirnya akan berimplikasi pada kedinamisan masyarakat
Indonesia, pada agama-agama ketika menyelesaikan konflik yang ada.
Nazar Nurdin, peneliti di Walisongo Reseach Institut Semarang